Seharusnya bukan namanya yang tercetak di undangan bertinta emas itu. Bukan dia yang menjadi pengantin hari ini, tapi aku. Tak taukah dia rasa sakit yang aku rasakan? Aku cinta dia, tapi kenapa dia tak pernah melihatku sedikit pun. Kenapa dia memilih meletakkan hatinya untuknya bukan untukku? Aku tau, aku hanya pengganti untuknya. Pernikahan ini pun seharusnya antara dia dan pilihan hatinya bukan denganku. Wanita itu pergi selamanya dari hidupnya dan dua minggu yang lalu, ia memintaku untuk menggantikan posisi wanitanya saat pernikahannya berlangsung. Tuhan, apa salahku selama ini padanya?
“Gue
mau mandi habis itu gue mau tidur. Siapin baju gue. Gue nggak mau tau, begitu
gue balik ke kamar ini, semuanya udah siap. O ya, satu lagi, loe tidur di sofa.
Gue nggak mau tidur bareng sama loe di tempat tidur. Ngerti?”
“Iya,
aku ngerti. Nanti aku siapin keperluan kamu. Terima kasih”.
Tak
lama dia pun keluar dari kamar ini, hingga saat ini aku tak berani menyebutnya ‘kamar
kami’. Karena memang ini bukan ‘kamar kami’. Aku bahkan tak punya lemari
disini. Semua bajuku masih tersimpan rapi di dalam koper. Aku tak punya benda
apa pun di kamar ini bahkan di rumah ini sekalipun. Semua miliknya dan wanita
yang seharusnya menikah dengannya. Aku hanya pengganti saja, dia pun hanya
menganggapku seperti itu. Kalau kalian bertanya, hubungan dalam rumah tangga
kami? Aku akan jawab, tak ada hubungan apapun. Sentuhan pun tak ada. Apalagi panggilan
sayang, tak pernah ada. Bagaimana dia memanggilku? Namaku yang dia panggil
dengan nada tinggi itupun hanya sesekali, selebihnya tak pernah dia menyebut
namaku. Hanya kesan dingin di dalam rumah tangga kami.
Dalam
diam aku menyiapkan segala keperluannya. Aku menyanggupi keinginannya yang tak
menginginkan aku tidur bersama dengannya dalam satu tempat tidur. Aku mengalah
memilih menurutinya. Biarlah seperti ini, walaupun sakit, aku rela karena aku
mencintainya.
Satu bulan kemudian
“Alya,
Marcel, kalian kapan mau kasih mama cucu? Mama udah nggak sabar pingin gendong
cucu”.
Aku
pun juga ingin punya anak dari dia, ma. Tapi, kalau tak ada hubungan apapun
dalam rumah tangga kami, aku bisa apa. Setidaknya jika aku memiliki anak
dengannya, aku masih punya alasan untuk tetap menahannya disisiku. Saat aku
hendak menjawab pertanyaan mamanya, dia mendahuluiku.
“Mama
sayang, bukannya Marcel sama Alya nggak mau kasih mama cucu cepet. Tapi, mama
kan tau kami baru nikah sebulan dan mama juga tau kan alasan di balik
pernikahan kami?”
Aku
melihat mamanya menghela nafas panjang. Seolah-olah beliau tak setuju mendengar
jawaban anaknya.
“Iya,
Marcel, mama tau apa alasan dibalik pernikahan ini. Tapi, tak bisakah kamu mempertimbangkan
keinginan mamamu ini, huh?”
“Oke,
ma. Kalau memang mama pingin banget cepet gendong cucu. Nanti kami usahain buat
cepet kasih mama cucu yaa. Ya udah, sekarang kami pulang dulu, biar kami bisa
segera kasih mama cucu. Setuju, ma?”
Aku
hanya bisa diam dan tak menjawab ajakannya saat dia mengajakku pulang ke
rumahnya.
--- 000 ---
Sore
itu di café Bintang, aku bertemu dengan sahabatku, Bintang, pemilik café ini. Kuceritakan
semua yang aku alami selama ini padanya. Dan dari yang aku lihat, Bintang marah
mendengar ceritaku.
“Al,
loe gila yaa. Masa loe mau aja sih digituin sama suami loe. Pertimbangin lagi,
al, perasaan loe. Belum cukup apa perlakuan dia ke loe dari dulu sampai saat
wanita itu pergi?”
“Gue
bisa apa, Bin? Gue cinta sama dia. Dari dulu sampai sekarang, dan itu nggak
berubah. Aku sadar, aku yang salah dalam kejadian itu. Tapi, aku bisa apa. Aku hanya
berusaha melindungi diriku sendiri. Nggak seharusnya aku datang hari itu”.
Aku
terisak menangisi semua kejadian beberapa bulan belakangan ini. Kejadian saat
Rachel meninggal, saat aku mengiyakan keinginan Marcel untuk menikah
menggantikan posisi Rachel di atas pelaminan, kehidupan rumah tanggaku,
keinginan mamanya. Semua kejadian itu berputar ulang di dalam kepalaku. Hingga gelap
itu datang menyerangku.
“Hei,
loe udah sadar, Al? Gue panggilin dokter dulu ya. Loe istirahat dulu aja. Sebentar
yaa, Al”.
Tak
lama dokter yang dipanggil Bintang pun datang. Dia suami Bintang, Aldo.
“Hai,
Al. Gimana keadaan loe? Apa yang loe rasain saat ini? Jangan minta pulang dulu
ya. Paling nggak besok baru loe boleh pulang. Nggak usah ngebantah. Siapa yang
dokter disini?”
Aku
tertawa mendengar pertanyaan dan ancaman Aldo. Bisa apa aku selain mengiyakan
keinginan suami sahabatku ini. Daripada aku ditoyor sama istrinya bisa panjang
nanti urusannya.
“Oke,
gue ikutin saran loe kali ini, Al. Gue nggak apa-apa kok, cuma masih pusing aja”.
“Ya
udah, loe sekarang istirahat gih, nanti habis makan, loe minum obatnya yaa. Tenang
aja, ada gue sama istri gue yang paling cantik di seluruh dunia yang bakalan
nemenin loe malam ini”.
“Nggak
usah ditemenin, Al, Bin. Gue nggak apa-apa kok sendiri disini. Gue jamin, gue
bakalan baik-baik aja. Percaya deh sama gue”, pintaku meyakinkan mereka berdua.
“Fine!
Kalo loe nggak mau kita berdua temenin. Tapi, paling tidak, makan dulu habis
itu minum obat. Setelah loe minum obat, kita berdua bakalan pulang, biar cepet
kasih loe ponakan”.
Fix!
Sahabat-sahabat aku ini pada gila semua. Bisa-bisanya ngomong sevulgar itu sama
aku. Tapi, gimana caranya aku ngomong ke Marcel ya? Bisa ngamuk dia kalau tau
aku nggak ada dirumah. Atau mungkin dia malah senang aku tak ada dirumah? Daripada
berspekulasi tak jelas, lebih baik aku menelponnya.
“Hallo,
Cel. Ini aku, Alya. Maaf, mala mini aku nggak pulang. Aku tidur ditempat
Bintang. Dia sendirian dirumah, suaminya lagi dinas malam. Terima kasih, Marcel”.
“Heh,
ngga usah pulang kerumah sekalian! Udah punya suami masih aja kelayapan nggak
jelas gitu”.
Percakapan
itu pun diputus sepihak olehnya. Aku terdiam mencerna setiap kalimat yang dia
ucapkan. Apa maksudnya memintaku tak pulang kerumah karena aku menginap di
rumah Bintang? Kalau dia tau aku lagi sakit seperti ini, apa yang akan dia katakan
ya? Apakah akan sama ataukah berbeda?
Kuputuskan
besok pagi-pagi sekali, aku keluar dari rumah sakit ini. Sudah kupikirkan
matang-matang. Dia memintaku untuk tak pulang kerumah. Aku tak akan pulang. Aku
akan pergi sejauh mungkin meninggalkan dia disini dan semua kenangan selama
beberapa bulan ini. Dua sahabatku pun tak akan kuberitau kemana aku akan pergi.
“Suster,
maaf, dimana pasien di kamar ini? Kenapa dia tak ada di kamarnya?”
“Maaf,
dok, tadi pagi-pagi sekali, mbaknya sudah keluar. Katanya mau pulang
kerumahnya, nggak enak sama suaminya, dok”.
“Yang,
gimana, Alya kemana? Dia nggak apa-apa kan? Dia baik-baik aja kan?”
“Sayang,
kamu tenang dulu yaa. Alya katanya udah pulang tadi kerumahnya. Kamu mau kita
kerumahnya?”
“Iya,
yang. Aku khawatir sama keadaan Alya”.
Tak
lama tibalah mereka berdua di apartemen milik Marcel suami Alya.
“Permisi,
Marcel, boleh kami ketemu Alya?”
“Kalian
siapa? Apa hubungan kalian sama Alya?”
“Perkenalkan
saya Aldo dan ini istri saya Bintang. Kami berdua sahabatnya Alya. Boleh kami
bertemu dengan Alya?”
“Alya
nggak ada disini. Semalam dia bilang, dia tidur di rumah kalian. Katanya suaminya
Bintang sedang dinas malam dan Bintang sendirian”.
“Ap-apa?
Nggak mungkin. Alya semalam tidur di rumah sakit, dia sakit. Dia kemarin
pingsan sewaktu di café saya. Saya membawanya ke rumah sakit tempat suami saya
bekerja. Kemana Alya? Jawab!”
“Yang,
sabar, yang. Sabar. Kita pasti ketemu sama Alya. Kamu yang tenang yaa”.
“Al-alya
sakit? Ta-tapi, dia semalam bilang… Oh,
shit! Apa yang udah gue bilang sama dia”.
Berbagai
pertanyaan menghampiri benak dua sejoli itu. Hingga mereka pamit pulang pun,
tak ada kalimat yang keluar dari mulut Marcel.
Dua bulan berlalu
Walaupun
masih terasa ada yang kosong di hati dan di sampingku, setidaknya, sekarang aku
sudah bisa tersenyum. Walaupun harus menahan rindu untuk tak bertemu dengannya.
Setidaknya aku sudah menuruti keinginannya untuk tak kembali lagi kerumah. Sungguh,
aku tak berharap dia akan merasa kehilanganku dan mencariku. Aku tak pernah
berharap sama sekali. Kalau dia bahagia dengan ketidakhadiranku, aku juga ikut
bahagia.
“Mbak,
dipanggil Mbak Marsha diruangannya,” panggilan Chyntia membuyarkan lamunanku.
“Oke,
Chyn. Sebentar lagi aku kesana. Makasih ya.”
Tok tok tok
“Nyariin
aku, Sha? Ada apa?”
“Desain
yang aku minta kemarin, udah selesaikah? Kliennya pingin liat dulu. Ribet banget
dia. Wajahnya sih cakep walaupun lebih cakep Bian sih, cuma dia kelihatan kacau
aja. Nggak ngerti lagi ada masalah apaan”.
“Udah
aku kirim email yaa, Sha, tadi pagi. Aku udah titipin ke Chyntia juga buat
dikasihin ke kamu”.
“Bentar,
Al. Klien yang kacau telpon. Iya, hallo..”.
“Al,
kamu bisa aku mintain tolong nggak? Klien kita ini pingin ketemu langsung sama
yang ngedesain. Kamu mau kan ketemuan sama dia? Bawa semprotan merica, Al, kalau
dia ngamuk, semprotin aja, habis itu langsung kabur”.
“Oke,
Sha, aku ketempat ketemuannya. Dimana?”
Café
di dekat kantor tempatku bekerja dan bersembunyi selama ini. Klien yang kacau
meminta untuk bertemu disini. Sebelum dia datang, lebih baik aku memesan minum
terlebih dahulu.
“Selamat
siang”
Suara
itu, nggak mungkin dia ada disini. Bukan dia kan yang menyapaku. Ini hanya
ilusiku saja kan? Kudongakkan kepalaku dan terkejut tatkala melihat dia yang
ada di hadapanku saat ini. Marcel! Apa yang terjadi sama dia, kenapa dia
sekacau ini?
“Al-alya?
Is that you? Oh God, kamu selama ini disini? Aku nyari kamu, Al. Demi Tuhan,
Alya. Aku takut kamu kenapa-kenapa. Kenapa kamu nggak bilang malam itu kalau
kamu sakit? Kenapa kamu mesti bohongin aku?”
Pelukannya
membuat aku menegang. Mendengar kata-katanya aku bertambah terkejut. Hei,
kemana panggilan ‘loe-gue’ yang selama ini dia pakai? Kenapa dia beraku-kamu
sekarang. Apa yang terjadi selama ini?
“Bisakah
kamu melepaskanku? Aku tak bisa bernafas”, pintaku lirih.
“Maaf,
Al, maaf. Kita cari tempat lain saja ya, nggak enak dilihatin banyak orang
gini? Kita ke apartemen aja ya. DO aja nggak apa-apa kan?”
Aku
hanya diam dan mengikutinya berjalan. Setelah membayar minuman yang tadi aku
pesan dan belu sempat kuminum, kuikuti langkahnya menuju parkiran. Mobil itu
pun melaju menuju ke apartemennya. Sekali lagi, apartemennya, bukan apartemen
kami. Bukan rumah kami, melainkan rumahnya, tempat tinggalnya.
Sesampainya
kami disana, dia segera memesan makanan Jepang dan Pizza. Kami hanya diam tanpa
berniat sedikit pun untuk memulai pembicaraan. Tak lama kemudian, pesanannya
pun datang. Kami makan dalam diam. Tanpa suara ataupun canda tawa. Hingga
makanan kami habis, tak ada niatan satupun dari aku untuk memulai percakapan
dengannya. Jujur, aku lelah. Aku lelah berspekulasi tentang dia. Hingga akhirnya
suara itu terdengar lagi. Dan kali ini sangat lembut.
“Alya,
kamu apa kabar? Kamu kemana aja, Al? Jadi, selama ini kamu bekerja di kantor
Marsha? Dan kamu yang ngedesain apa yang aku minta? Jawab, Al. Jangan hanya
diam saja”.
“Kabar
aku baik. Terima kasih. Aku nggak kemana-kemana kok, aku masih di kota ini. Aku
bekerja sama Marsha dan iya aku yang mendesain permintaan kamu. Maaf, kalau
kamu kecewa dengan apa yang aku kerjakan”.
“Syukurlah
kamu baik-baik saja. Aku mencarimu, Al. Aku hampir putus asa mencarimu. Au bahkan
tak tau jika kamu ternyata amat sangat dekat denganku. Tidak, Al. Tentu saja,
tidak. Aku suka dengan apa yang kamu kerjakan. Sangat indah, Al. Terima kasih”.
Apa
katanya? Terima kasih? Aku tak salah dengar kan? Dia mencariku? Karena inikah
dia menjadi kacau seperti ini? Tuhan, ada apa ini sebenarnya?
“Ka-kamu
mencariku? Kenapa? Bukankah kamu tak menginginkan aku kembali kesini?”
“Maafkan
aku, Al. Aku salah. Tolong, maafkan aku. Harusnya aku tak perlu bersikap dan
berbicara kasar padamu. Aku tak tau jika selama ini kamu begitu amat tersakiti
dengan sikapku. Harusnya malam itu aku tak perlu berbicara kasar seperi itu
padamu. Tapi, malam itu aku bingung, kamu tak pulang kerumah dan hanya telpon
sekali mengabarkan kamu di rumah sahabatmu yang bahkan aku tak mengenalnya. Kamu
pergi ketempat dia juga tak pamit padaku. Malam itu, aku marah, aku kecewa. Hingga
aku mengatakan hal yang membuatku kehilanganmu. Maafkan aku, Al. Harusnya malam
itu kamu bilang kalau kamu sakit. Kalau sahabat-sahabatmu tak mencarimu kesini,
aku tak akan tau jika kamu sakit dan pergi dari rumah sakit. Maafkan aku, Al,
maafkan semua sikapku selama ini padamu.”
Dia
menangis, berlutut di hadapanku memohon maaf. Apa yang harus aku lakukan? Aku bingung.
“Jangan
pergi lagi, Al. Aku mohon. Jangan pergi lagi. Aku kacau tanpamu, Al. Aku nggak
sanggup jika harus kehilanganmu lagi, Al. Aku mohon, jangan pergi lagi, Al.
Jangan tinggalkan aku sendiri. Aku mencintaimu, Al. Aku sungguh-sungguh
mencintaimu. Maafkan aku, yang tak pernah jujur padamu.”
Apa
dia bilang? Dia mencintaiku? Inikah akhir dari kisah sedihku? Haruskah kumaafkan
dia? Haruskah aku bahagia? Perlahan, kupeluk tubuhnya, kutenangkan dia.
Kutangkup wajahnya, kuhapus air matanya.
“Jangan
menangis lagi, Cel. Aku memaafkanmu. Sebelum kau meminta maaf, aku sudah
memaafkanmu. Aku tak akan pergi. Berjanjilah, jangan bersikap seperti itu lagi
padaku.”
Aku
menangis. Ingin kukeluarkan semua beban di hatiku, tapi aku tak sanggup. Kuharap
lewat tatapan mataku, dia bisa mengetahui apa yang aku rasakan. Aku mencintainya,
terlalu mencintainya.
“Soal
Rachel. Tak seharusnya aku menyalahkanmu. Itu bukan salahmu, Al. Keadaan yang
membuat dia seperti itu. Aku tak tau kalau dia yang selama ini mencelakaimu. Aku
tak sudi jika harus menikah dengan dia. Aku bersyukur dia tak ada lagi. Mama hampir
masuk rumah sakit karena diancam olehnya. Kenapa kamu tak bilang padaku kalau
dia tak baik padamu, huh? Dari awal hingga nanti maut memisahkan kita, kamu
milikku, Al. Selamanya milikku. Aku tak pernah mencintai Rachel. Aku bersamanya
karena dia memaksaku. Wanita itu benar-benar gila. Maafkan aku yang tak bisa
melindungimu selama ini.”
“Hari
dimana kejadian itu terjadi, sebenarnya aku sedang mempersiapkan lamaran romantis
untukmu. Tapi, tak kusangka, dia mengetahuinya. Entah dengan tipu daya apa, dia
berhasil memintamu datang, dan hampir membuatmu celaka. Dan beruntunglah bukan
kamu yang meninggal, tapi dia. Aku mengkhawatirkanmu, Al, kamu tak bisa
kuhubungi dan tiba-tiba polisi menghubungki, mengabarkan kamu ada di kantor
polisi. Aku panik, Al. Kamu tau sendirikan, gimana kalau aku panik, aku
marah-marah tak jelas. Undangan itu pun bukan aku yang membuatnya. Itu akal-akalan
dia, Al. Dia tak ingin apa yang dia suka menjadi milik orang lain. Itulah kenapa
dua minggu setelah kematiannya, aku nekat memintamu untuk menjadi istriku. Mungkin
saat itu kamu berpikir kamu menjadi penggantinya. Aku tak pernah memintamu
untuk menjadi penggantinya. Selamanya kamu adalah istriku, milikku. Bukan pengganti
siapa-siapa. Padamu aku memilih meletakkan hatiku, Al. I Love You, baby.”
Aku
menangis mendengar pengakuannya. Kucari di kedua matanya kebohongan dari
pengakuannya. Tapi, tak kutemukan. Yang kutemukan hanya kejujuran, kelegaan,
dan cinta. Hah? Cinta? Benarkah ini? Dia meraihku ke dalam pelukannya,
menenangkanku yang tak berhenti menangis.
“Jangan
menangis lagi, Al. Aku tak sanggup melihatmu menangis seperti ini. Katakan
padaku, Al, apa yang kamu rasakan padaku?”
“Aku..
hiks.. hiks.. aku sungguh tak tau jika kamu mencintaiku sedalam itu. Jika kamu
tak pernah menjadikanku pengganti dalam hidupmu.. hiks.. Aku juga mencintaimu,
Marcel.”
Terucaplah
sudah apa yang aku rasakan selama ini. Dia tersenyum senang. Tatapan matanya
yang tadinya lembut perlahan berubah menjadi tatapan lapar. Eh? Kenapa dia
menatapku seperti itu? Aku bukan makanan kan? Apa dia masih lapar? Kenapa tatapannya
berubah menjadi lapar begitu?
“Alya,
karena semua permasalahan diantara kita sudah selesai. Dan aku tak ingin kamu
menangis sedih lagi. Bolehkah hari ini kuminta hakku sebagai seorang suami? Mulai
hari ini, apartemen ini dan segala miliknya adalah milik kita berdua. Kamu boleh
mendesainnya, boleh mengaturnya. Kamar itu milik kita. Semuanya milik kita. Aku
tak akan melarangmu bekerja, tapi kumohon jangan melebihi jam kerjaku. Aku ingin
pulang disambut istriku.”
Aku
tertawa kecil mendengar permintaannya. Sudah saatnyakah aku memberikan haknya
sebagai suami? Aku hanya mengangguk mengiyakan permintaannya. Dan hari itu,
hari bersejarah untuk kami. Ikatan yang sempat hampir putus kembali terajut. Dan
ikatan itu akan membentuk sebuah ikatan baru dalam keluarga kami. Dan aku harap
itu selamanya.
--- 000 ---
Nikmatilah hari ini dengan
penuh pengharapan. Karena kita tidak tau apa yang akan terjadi esok hari.
-
Alya & Marcel –
--- 000 ---
28
Januari 2015
Ide
dari cerita ini terlintas begitu saja di otakku sewaktu perjalanan kembali ke
rumah. Hanya menuangkannya ke dalam cerita dan percakapan yang lumayan agak
susah.
Aku
dedikasiin buat mbak Ikadelia. Lagi
greget banget sama ceritanya Disty-Aldo. Konfliknya jangan parah-parah yaaa,
mba. Bisa nangis bombay nanti saya :)
Selamat
membaca, semua :) semoga kalian suka yaaa









.png)
.png)
.png)
.png)
.png)


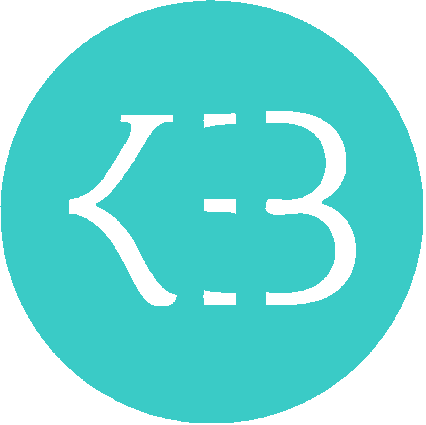









suka nih kalo endingnya begini hehe
ReplyDeleteHappy ending yaa, mba? hehehe... Tapi, saya pas nulis, malah sakit hati sendiri, terlalu mendalami sepertinya hehehe
Deleteseru :)
ReplyDeleteTerima kasih, mba :)
Delete